Berziarah ke pemakaman Gunung Jati, Cirebon, akan dikepung oleh segerombolan bocah, dan terkadang orang tua pun menyertainya, terlebih lagi memasuki hari-hari besar Islam seperti bulan Mulud. Mereka terus menempel memaksa pengunjung mengeluarkan beberapa lembar pecahan uang kecil atau recehan.
Pemandangan semacam itu bukan hanya di pemakaman Gunung Jati, melainkan di beberapa tempat lain juga, terutama di masjid-masjid pada bada salat jumat. Di area keraton-keraton Cirebon pun begitu, mereka ada di sana.
Awal kemunculan fenomena meminta-minta (mengemis) belum diketahui persis, tetapi ditengarai berlangsung sejak beberapa abad lalu. Sebuah historiografi tradisional paling popular di kalangan masyarakat Cirebon dan Indramayu, naskah Babad Cirebon, di dalamnya terdapat penggalan kisah seorang pengemis di Lemah Wungkuk Cirebon pada abad ke-15. Nama si pengemis Syarif Durakman, nama lain dari Sunan Kalijaga. Tujuan utamanya ingin bertemu dengan Sunan Gunung Jati, menjadi pengemis hanya menyamar.
Wasiat Sunan Gunung Jati
Isun Nitip Tajug lan Fakir Miskin, "Saya menitipkan musolla dan fakir miskin". Bagi masyarakat Cirebon ungkapan berbahasa Jawa (dialek Cirebon) itu tidak begitu asing. Masyarakat meyakininya sebagai wasiat Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati khusunya kepada masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Tujuannya supaya umat Islam mau menghidupi atau merawat masjid serta mengasihi kaum fakir dan miskin.
Menitipkan masjid bisa dimaknai sebagai pesan tersirat yang memiliki tujuan supaya umat muslim menjalankan salat di masjid secara berjamaah. Sebab, fungsi masjid sejak beberapa waktu lalu lebih dari sekedar tempat salat tetapi sekaligus menjadi pusat kegiatan belajar, bahkan politik. Keraton sebagai pusat politik dan pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi pun dibangun berdekatan dengan masjid. Beberapa keraton di Jawa, seperti keraton Majapahit, Yogyakarta, dan Cirebon, membuktikan hal itu.
Sementara itu, menitipkan fakir miskin, bisa dimaknai supaya umat muslim memiliki perhatian atas orang-orang miskin, mengasihi mereka yang hidupnya serba kekurangan. Mereka berhak mendapatkan zakat atau sedekah dari orang yang lebih mampu.
Nah, keberadaan mereka itu mengiringi perkembangan Kota Wali dari awal perkembangannya hingga saat ini. Negara memberi amanat atas orang-orang fakir dan miskin dalam pasal 34 UUD 1945 ayat 1, "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara". Hanya saja, kedudukan UU tersebut tidak sesakral wasiat Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati. Definisi orang-orang miskin kemudian mengalami penyempitan makna, menjadi pengemis.
Ada yang berpendapat bahwa Isun Nitip Tajug lan Fakir Miskin murni perkataan dari seorang kemit (penjaga makam Sunan Gunung Jati). Tetapi mungkin juga bahwa ungkapan itu betul-betul perkataan Sunan Gunung Jati, hanya saja tidak pernah tertuliskan. Faktanya, kita tahu bahwa ada banyak ungkapan atau cerita yang hanya berkembang secara lisan (oral tradition) tanpa memiliki catatan tertulisnya. Titik persoalannya, bukan pada siapa yang mengatakannya melainkan apa isi perkataannya, dengan kalimat lain dampak sosial yang ditimbulkan dari ungkapan itu.
Kearifan Lokal atau Ketidakarifan Lokal
Kebudayaan pada setiap wujudnya menyimpan berribu kearifan lokal. Kearifan lokal sangat mujarab untuk menangkal atau menyaring tindakan destruktif, tindakan amoral, pengaruh negatif dari luar, atau segala yang bertentangan dengan agama atau budaya. Kearifan lokal tetap terpelihara karena bernilai baik. Tetapi dalam kebudayaan juga terdapat ketidakarifan lokal. Isun Nitip Tajug lan Fakir Miskin bernilai baik hanya pada satu sisi, dan pada sisi yang lainnya perlu diuji lagi. Perlu juga diketemukan konteks yang melatarinya, karena hal itu terikat oleh ruang budaya dan waktu.
Kini ungkapan menitipkan masjid dan fakir miskin terus dikukuhkan dan dipribumikan, hingga menyebar luas menyentuh alam bawah sadar bagi siapa pun yang mendengarnya. Bagi yang meyakininya akan memperoleh kekuatan dan jalan hidupnya akan dimudahkan; bagi yang meragukannya tidak mendapatkan apa-apa atau bahkan kutukan (celaka).
Konon katanya, jika ingin cita-citanya terwujud, harapannya kelakon 'tercapai', perlu berikhtiar dengan berziarah ke makam Sunan Gunung Jati terutama di bulan Mulud, untuk melakukan ritual suci atau sekedar bertawasul. Namun, tidak mudah untuk sampai ke hadapan makam Kanjeng Sinuhun. Salah satu syarat yang harus dipenuhi yaitu membawa sebanyak mungkin uang receh, atau beberapa lembar uang pecahan kecil. Siapa pun yang meminta harus diberi, tidak boleh seorang pun ditolak. Jika di antara mereka merasa tidak senang karena yang diterima terlalu kecil atau memberinya setengah ikhlas, maka akan menjadi penghalang bagi cita-cita orang yang memberinya.
Paling tidak, jika ingin terhindar dari celaka (blai), lemparkan beberapa uang recehan di sudut pemakaman Sunan Gunung Jati. Di sana sekerumunan orang, dari yang paling muda sampai yang paling tua, sudah "memasang kuda-kuda", siap berebut dengan kawan-kawannya, seperti permainan Hoki.
Oleh karena tradisi ini sudah berjalan sangat lama, para pelaku memandangnya sebagai hal yang lumrah. Barangkali bagi mereka berebut uang receh, mengharap belas kasih, atau apapun wujudnya, bukan lagi sebagai aib melainkan sebagai profesi, yang terkadang pendapatannya lebih menggiurkan daripada pekerjaan lainnya. Tradisi semacam itu terus diwariskan ke generasi berikutnya, ke anak cucu. Nah, eksistensi mereka tetap terpelihara oleh orang-orang yang meyakini ungkapan itu. Dan kini, dengan aneka bentuk dan modus, fenomena mengemis turut menyertai perkembangan Kota Wali.
Legitimasi Sosial
Rupanya, pejabat keraton pun tidak sedikit yang bermain-main, mengambil bagian dari praktik itu, meminta-minta ke pengunjung yang berhasrat besar ingin berziarah ke makam Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati. Hanya saja, caranya lebih 'ekslusif', namun substansinya sama. Upeti yang harus ditanggung terkadang tidak masuk di akal, suatu profesionalisme model baru dan terus mengalami inovasi, dan mungkin juga akan langgeng.
Para pengemis pun mendapatkan legitimasinya dari mereka, ketika menyaksikan praktik lancung yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Mereka yang kebanyakan elit keraton secara tidak langsung menjadi mesin yang mereproduksi kebiasaan tidak wajar itu, kemudian diikuti oleh masyarakat di bawahnya. Mental semacam itu tampaknya warisan dari zaman kolonial Belanda, ketika diberlakukan sistem gaji. Oleh pemerintah Hindia Belanda, pejabat-pejabat keraton tak ubahnya dengan Pegawai Negeri Sipil.
Lebih jauh lagi, menitipkan tajuk dan fakir miskin memiliki kekuatan melegitimasi, bahwa keberadaan para pengemis mesti diakui sekaligus dipelihara. Jadi, ungkapan itu menjadi penguat konstruksi sosial pada lapisan terbawah, terutama yang ditempati oleh para pengemis. Fenomena mengemis pada akhirnya dipandang bukan sebagai suatu problem sosial yang harus ditemukan akar permasalahannya. Mereka seakan dianggap sebagai warisan budaya yang perlu dipelihara kelestariannya.
Oleh karena itu, perlu diciptakan suatu tatanan sosial, memberikan pilihan habitus kepada meraka, menegaskan bahwa mengemis buka takdir Tuhan yang tidak bisa diubah. Membutuhkan political will untuk meminimalisir atau menghilangkan itu semua, jika memang dianggap sebagai problem sosial yang menjadi masalah bersama.
Artikel dipublikasikan dalam Pelestari Budaya Nusantara Adiluhung, Edisi 17/2018
Penulis adalah filolog dan Direktur Cirebonese Fondation
elanglangitmendung@gmail.com
087828978759
Advertisement
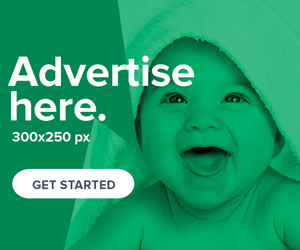
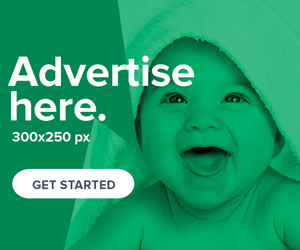



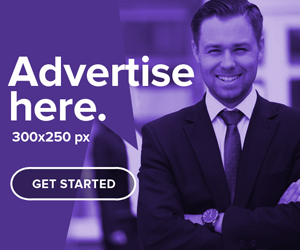
EmoticonEmoticon