oleh Nurhata
Pertunjukan wayang dan Sandiwara adalah tradisi Jawa Kuna yang kini tetap survive di tengah derasnya arus globalisasi. Tradisi itu memiliki akar yang begitu panjang, beberapa abad sebelum Wali Sanga memperkenalkan Islam ke penduduk Jawa. Adapun mengenai asal-usulnya, kesenian itu pure dari tanah Jawa, meskipun pada awal kemunculannya melakonkan epos dari India.
Di dalam kesusastraan Jawa Kuna, pada abad ke-10, terminologi wayang banyak dijumpai baik sebagai analogi maupun hanya sebuah deskripsi. Keberadaan wayang yang memiliki nama lain ringgit, pada masanya sudah melekat kuat di dada masyarakat, begitu digandrungi. Zoetmulder (1983) dalam Kalangwan, menguraikan: "Bhima Kumara pernah digunakan sebagai naskah pertunjukan wayang; Hariwangsa untuk pertunjukan wayang orang; dan Ramayana sebagai kitab kidungan. Informasi tertua ia menunjuk pada prasasti Raja Balitung berangka tahun 907".
Di Cirebon (juga Indramayu), sebagai salah satu daerah yang mewarisi tradisi itu, pertunjukan wayang menduduki posisi terpenting di antara kesenian rakyat lainnya. Di setiap upacara adat, pertunjukan wayang tidak hanya sebagai “tontonan” dan “tuntunan” melainkan sebagai syarat bagi proses berlangsunya upacara adat. Tanpa pertunjukan itu, upacara adat seperti Mapag Sri, Nyadran, dan Unjungan, seakan tidak sah.
Wayang
Wayang
Anggapan umum, khususnya masyarakat Cirebon dan Indramayu, wayang (purwa) adalah kreasi Sunan Kalijaga. Sumber kuna yang kerap disebut adalah bagian akhir dari teks Babad Cirebon atau Cariyos Walangsungsang, menceritakan Sunan Kalijaga membuat wayang di Gunung Dieng. Sebelum membuat wayang, ia mensketsa terlebih dahulu di atas tanah. Naskah yang berkisah pembuatan wayang itu mengalami peningkatan jumlah luar biasa, disalin puluhan kali oleh pujangga keraton dan dalang wayang. Bahkan, masyarakat awam yang jauh dari pusat kekuasaan pun, memiliki apresiasi tinggi atas karya itu: menyalin dan mendeklamasikannya. Tidak heran jika asumsi itu terus diamini, menjadi kebenaran mainstream. Padahal, beberapa abad sebelumnya, seni pertunjukan itu sudah dikenal di seluruh lapisan masyarakat Jawa Kuna.
Penjelasan lebih detail perihal jenis wayang buatan wali yang memiliki nama lain Pangeran Jagabaya itu tidak diuraikan dalam naskah. Sebagai hipotesa, jenis wayang yang dimaksud berupa wayang golek karena, kepergiannya ke Gunung Dieng dalam rangka proses penyucian jiwa: sebagai petapa. Sebagaimana petapa pada umumnya, membunuh binatang apapun untuk diambil kulitnya atau memakan daging binatang adalah perbuatan yang harus dijauhi. Dengan kalimat lain tidak ada praktik pengulitan seekor binatang, kerbau misalnya, untuk dijadikan wayang. Pertapaannya boleh juga dimaknai sebagai ijtihad dalam mengubah jenis wayang kulit menjadi golek (kayu) sebagai gerbang bagi masuknya Islam di tanah Jawa. Usaha kerasnya tak sia-sia, berhasil mengubah keyakinan masyarakat Jawa tanpa perlawanan berarti. Cerita ini kemudian berkembang di tengah masyarakat, menjadi taradisi tutur yang terus terjaga hingga beberapa abad kemudian, sampai saat ini.
Penyusunan naskah Babad Cirebon bersumber dari naskah Purwaka Caruban Nagari (ditulis tahun 1720) karya Pangeran Arya Carbon. Ditengarai, naskah Babad Cirebon tertua, yang warna Islamnya begitu kental, ditulis beberapa tahun belakangan setelah Purwaka Caruban Nagari, atau sekitar akhir abad ke-18, di saat Islam sudah mapan. Perihal demikian dapat dipertegas oleh pernyataan Pigeaud, bahwa menurutnya dari abad ke-16 sampai abad ke-18, adalah masa di mana gerakan penyalinan naskah yang bernafaskan Islam berlangsung secara massal.
Di Indramayu, pertunjukan wayang kulit dan wayang golek bergerak beriringan. Melalui lakon wiracarita Hindu-Budha, Jawa, dan Islam, kesenian itu tumbuh subur pada pertengahan abad ke-19. Kisah yang kental dengan unsur Islam, seperti Serat Menak, Adam Jalalah, Umar Maya, Serat Yusuf, Lamsijan, dan Durakman-Durakim, menempati posisi penting bagi pertumbuhan pemahaman keagamaan di daerah itu. Cerita-cerita tersebut lazim dijumpai dalam naskah koleksi dalang. Peran besar dalang dalam mengembangkan kesusastraan melalui tradisi penyalinan dan seni pertunjukan wayang tidak boleh dikesampingkan.
Dalam kesusastraan Islam, meskipun mengalami perkembangan signifikan tetapi tidak menenggelamkan cerita Hindu-Budha. Kisah peperangan antara Pandawa dan Korawa di Palagan Kurusetra serta kisah penculikan Sinta oleh Rahwana yang berujung pada penyerangan Ramadewa ke Kerajaan Alengka, tetap digemari. Demikian pula dengan Wiracarita Jawa, Ken Arok Ken Dedes dan Babad Tanah Jawa misalnya, tetap diminati oleh masyarakat.
Kini, lanjutan kesenian Jawa Kuna pertunjukan wayang lebih banyak lagi varian dan versinya, bentuk fisik (tokoh wayang) dan ceritanya pun beragam. Tokoh Punakawan tidak kalah populer dari tokoh Pandawa, begitu juga cerita Cungkring dadi Raja atau Semar Gugat Kadewatan tidak kalah menarik dari epos India. Variasi-variasi itu adalah sifat dari kebudayaan yang memang selalau bermetamorfosa sesuai dengan kebutuhan zamannya.
Sejak kemunculannya, terminologi wayang orang (wayang wwang) yang tumbuh-kembangnya beriringan dengan wayang kulit purwa Jawa Kuna, menyerupai Sandiwara. Lakon yang disampaikan, pada awalnya, memiliki banyak kesamaan dengan wayang kulit. Seni pertunjukan ini melibatkan sejumlah aktor, protagonis dan antagonis, mengandaikan sebuah plot dan latar. Unsur komedi dan tragedi, atau yang bernada satir kerap menyelinap dalam pertunjukan ini. Di samping cerita, tarian-tarian dan kidungan juga turut mengisi. Cerita kronik serta tema-tema yang bertalian dengan fenomena mutakhir, dalam perjalanannya lebih mendominasi, mengisi hampir setiap pertunjukan rakyat semacam ini. Perkembangan ke titik ini melahirkan suatu istilah yang disebut dengan Sandiwara atau Masres. Term Sandiwara sendiri tidak ada dalam perbendaharaan kata Jawa Kuna.
Dalam pementasan Sandiwara, naskah babad atau kronik biasanya dijadikan 'naskah' utama. Ricklefs (2007) menempatkan genre sastra tersebut sebagai sumber sejarah yang patut dirujuk, meskipun tidak semuanya, terutama karena banyaknya muatan-muatan irasional atau masalah hubungan-hubungan kausalitas. Urgensi naskah babad terlihat ketika kita mengungkap suatu sejarah sejarah. Misalnya, peristiwa pemberontakan Bagus Rangin, tanpa merujuk Babad Darmayu, akan menghasilkan kesimpulan yang jauh dari kadar obyektif menurut masyarakat pribumi. Tentunya, bukan hanya naskah babad, naskah jenis lain pun perlu disandingkan, termasuk arsip kolonial, tradisi tutur (lisan), dan bukti-bukti arkeologis lainnya, sebagai sumber primer yang juga mampu menunjang proses identifikasi jejak leluhur masyarakat Nusantara.
Pada prinsipnya, setiap tradisi terus mengalir, menggumpal, hingga menemukan bentuknya yang baru pada ruang-ruang tertentu. Namun tidak dipungkiri pula bahwa ada bagian-bagian yang hilang, bahkan mungkin juga sirna seluruhnya. Pertunjukan wayang dan Sandiwara yang kini mengiringi peradaban kita pun sedang dalam proses mencari formatnya. Dan, potensi akan hilang, tergantikan oleh sesuatu yang lebih menarik dan lebih menggoda, akan selalu ada, karena itu bagian dari sifat alaminya, apalagi di era postmodern sekarang ini.
muhammadnurhata@gmail.com
087828978759
*Terbit di surat kabar harian umum Fajar Cirebon pada hari Rabu, 3 Februari 2016
Advertisement
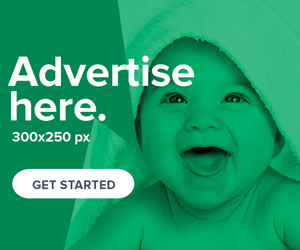
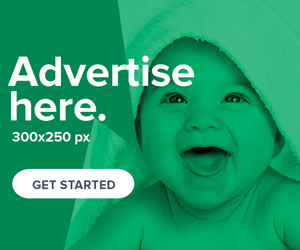



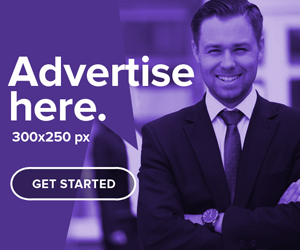
EmoticonEmoticon