Oleh Nurhata
Lagi,
pembakaran manuskrip terjadi di daerah Sumber, Cirebon, beberapa bulan lalu.
“Setiap selesai mempelajari isinya, saya langsung membakarnya”, demikian
pengakuan pemiliknya (mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya). Ia memiliki menuskrip satu lemari lebih, dan yang sudah dibakar kurang lebih satu saf (lemari). Merasa
penasaran dengan ceritanya, saya pun langsung meminta kepada pemilik untuk diantarkan
langsung ke tempat penyimpanannya, pada 11 Agustus 2014. Namun, ia hanya
memberikan beberapa manuskrip saja, “Tidak bisa diperlihatkan semuanya”,
katanya, dengana alasan amanat dari kakeknya. Hanya lima manuskrip yang boleh
diperlihatkan, itu pun yang tidak lengkap. Saya buka satu per satu, dan isinya
seperti kitab-kitab yang ada di pesantren: Imriti, Sorof, Alfiyah Ibn Malik, dan
Kitab Miraj. Semua manuskrip dalam keadaan tidak terawat, rusak, dan lapuk.
Alas manuskrip yang diganakan kertas eropa, terdapat cap kertas (watermark) di dalamnya, berupa binatang
dalam gambar melingkar. Salah satu penulis manuskrip itu adalah ayahanda Kiyai
Ayip Mu, Jagasatru, Cirebon.
 |
| gamabr diambil dari http://kabararkeologi.blogspot.com/2011/12/berita-ribuan-dokumen-langka-terbakar.html |
Apa
yang bisa kita lakukan menghadapi orang-orang seperti dia, yang pasti kita tidak
bisa menghakimi. Pemilik manuskrip, dengan segala keyakinannya, adalah
orang yang mewarisi catatan leluhur, pada satu sisi. Pada sisi yang lain,
mereka juga kerap menganggap cagar budaya itu dapat membahayakan orang lain,
meski dengan logika apapun sukar diterima oleh akal sehat kita (peneliti).
Artinya, harus ada upaya untuk memberikan pemahaman kepada mereka (pemilik)
tentang manuskrip-manuskrip koleksinya, bahwa manuskrip bukanlah benda klenik
yang dapat memberikan petaka bagi yang mempelajarinya atau bagi yang merawatnya.
Bahwa tujuan penulisan manuskrip yang dilakukan oleh leluhur kita tidak
dijadikannya sebagai benda yang dapat mengantarkan kesaktian atau sebaliknya
pada seseorang melainkan untuk dipelajari, dst, itu harus disampaikan ke pemilik. Akan tetapi, untuk mencapai
satu titik pemahaman itu perlu usaha keras dari banyak pihak, terutama
pemerintah.
Pokok
permasalahan yang paling besar sesuangguhnya ada pada tingkat apresiasi dari
pihak terkait (baik peneliti maupun pemerintah), bagaiamana cara menghargai
mereka yang menyimpan banyak manuskrip. Kita tidak bisa hanya mengunjungi,
mendokumentasikan, dan mencantumkan nama pemilik ketika kita melakukan
pendataan cagar budaya atau melakukan penelitian lainnya. Bagaimana hal ini menjadi
kesadaran di tingkatan pemegang kebijakan, yang diwujudkan menjadi pemberian
kesejahteraan bagi pemiliknya, misalnya dengan memberikan ruang yang memadai
atas koleksinya dan memberikan penghargaan berupa uang pemeliharaan. Jika hal
ini secepatnya dilakukan maka dapat menghentikan pembakaran manuskrip yang
hingga kini masih terus berlanjut. Fenomena pembakaran manuskrip adalah
fenomena gunung es, hanya sedikit saja yang kita ketihahui.
Sesungguhnya
pembakaran manuskrip bukan pertama kalinya terjadi di beberapa desa di
Indramayu dan Cirebon. Hampir, setiap kali saya mengunjungi para pemilik manuskrip,
saya mendengar cerita seperti itu. Bahkan, peristiwa serupa juga pernah terjadi sejak
beberapa abad silam (sekitar abad 14) di daerah Juntinyuat (sekarang masuk dalam
kecamatan Indramayu). Ketika itu Syekh Bentong yang membawa manuskrip satu perahu, kalah berdebat dengan Syekh Quro
tentang hakekat Iman dan Islam. Syekh Bentong menyuruh dua ajuadannya untuk membakar semua kitab yang ia bawa dari negeri seberang. Cerita itu diuraikan secara gamblang dalam manuskrip
Babad Cerbon.
Advertisement
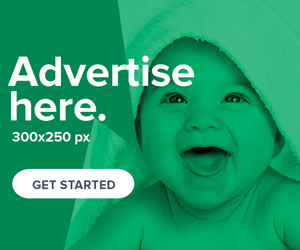
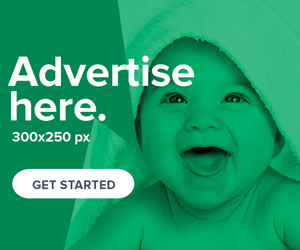


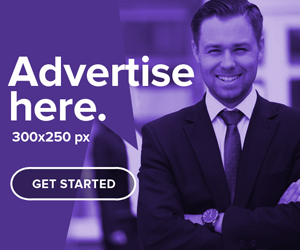
EmoticonEmoticon